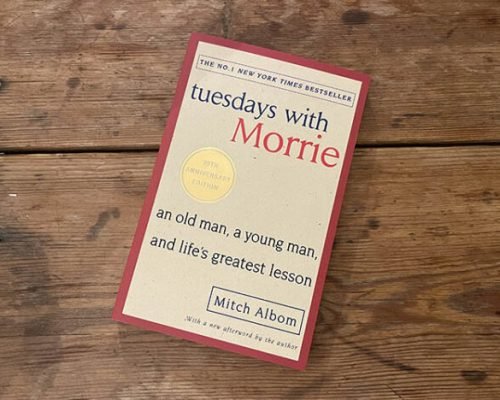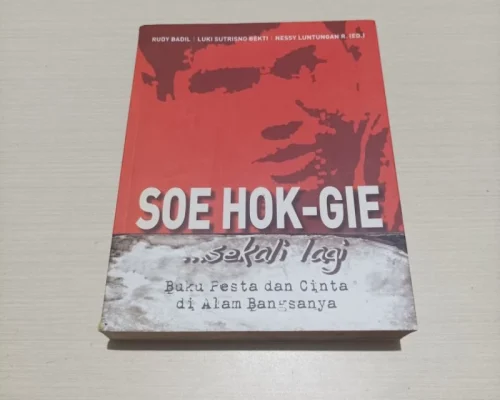The Strongman karya Gideon Rachman dan Fascism dari Madeleine Albright adalah dua buku bagus yang harus dibaca untuk memahami dilema politik dunia pada masa kini.
Kedua buku ini menjadi cermin yang memantulkan ambiguitas dunia politik. Pada satu sisi, rakusnya manusia pada kekuasaan. Pada sisi lain, kerapuhan manusia karena godaan kekuasaan itu sendiri. Meski pesannya hampir sama, kedua pengarang itu berbeda dalam cara mereka menelusuri jalan-jalan gelap politik yang bisa membawa dunia ke jurang kehancuran.
Di tangan Rachman, strongman muncul bagaikan sosok perkasa, berdiri di tengah badai krisis ekonomi, menggenggam janji stabilitas yang dinanti-nanti oleh rakyat yang dilanda kecemasan. Pemimpin ini menyalahgunakan sistem demokrasi, bersuara keras dan tegas, memikat massa yang lapar akan perubahan.
Sang pemimpin alias the strongman akan berseru, “Aku akan menyelamatkanmu,” namun di balik jubah kekuatan itu, tersembunyi pedang yang siap merobek institusi demokrasi, meruntuhkan kebebasan yang selama ini dijaga.
Rachman melihat bagaimana dunia modern, dengan globalisasi yang merenggut pekerjaan dan menciptakan kesenjangan, membuka jalan bagi mereka yang mengklaim diri sebagai pelindung rakyat.
Mereka hadir dengan janji yang memesona, namun di setiap langkah, mereka menghancurkan apa yang dulu dibangun: kebebasan pers, hukum yang adil, hak untuk memilih. Dalam dunia Rachman, strongman bukanlah tiran yang memaksa, melainkan sosok yang disambut dengan tangan terbuka, hingga akhirnya merampas segalanya.
Albright membawa kita ke lorong-lorong pengalaman masa lalunya, ke dunia di mana fasisme pertama kali muncul, membawa kengerian yang membakar bumi. Fasisme, dalam pandangan Albright, bukan sekadar ideologi yang ditandai dengan kekerasan dan perang, melainkan racun yang perlahan menyebar melalui retorika kebencian, pembatasan kebebasan, dan janji kekuatan yang palsu.
Fasisme lama datang dengan parade, simbol, dan slogan yang memekakkan telinga, namun, kata Albright, fasisme baru lebih halus, lebih licik, merayap melalui celah-celah ketakutan dan ketidakpuasan.
Albright memperingatkan bahwa fasisme bukanlah kenangan masa lalu. Ia hadir dalam wujud baru, merasuki dunia yang lelah dengan ketidakpastian. Fasisme modern tidak selalu mengenakan seragam atau menyulut perang, tetapi menggerogoti fondasi demokrasi dengan membatasi kebebasan berbicara, menumbuhkan kebencian pada minoritas, dan memanipulasi ketakutan akan perubahan.
Dalam dunia Albright, fasisme adalah bayangan gelap yang terus mengintai, siap bangkit kapan saja saat dunia lengah.
Di antara dua dunia ini, Rachman dan Albright berdiri sebagai pengingat. Mereka sama-sama memperingatkan kita akan bahaya pemimpin kuat yang datang dengan janji stabilitas di saat krisis.
Namun, perbedaan mereka terletak pada jalan yang mereka telusuri. Rachman melihat ke masa kini, pada pemimpin seperti Donald Trump, Vladimir Putin, atau Jair Bolsonaro—para pemimpin yang muncul dari krisis modern dan ketidakpuasan globalisasi. Mereka memegang kendali atas demokrasi, tetapi secara perlahan meruntuhkan pilar-pilar kebebasan dari dalam.
Sementara itu, Albright memandang lebih dalam ke sejarah. Dia mengingatkan kita bahwa bayangan fasisme tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin telah berubah bentuk, namun esensinya tetap sama—otoritarianisme yang mengancam kebebasan dan martabat manusia.
Dia memperingatkan bahwa demokrasi bisa hilang bukan hanya melalui perang, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang membawa kita semakin jauh dari kebebasan yang sesungguhnya.
Keduanya berbicara tentang kekuasaan yang terlalu besar, dan harga yang harus dibayar untuk kebebasan yang dikorbankan. Rachman berbicara tentang para strongman modern yang meraih kekuasaan melalui krisis, sementara Albright memperingatkan kita tentang fasisme yang terus mengintai, siap merasuki dunia yang lemah.
Dalam dua suara yang berbeda, mereka menyampaikan satu pesan yang sama: kewaspadaan adalah kunci agar kebebasan tetap hidup di dunia yang rapuh ini.
Pdt. Dr. Albertus Patty, Intelektual Kristen